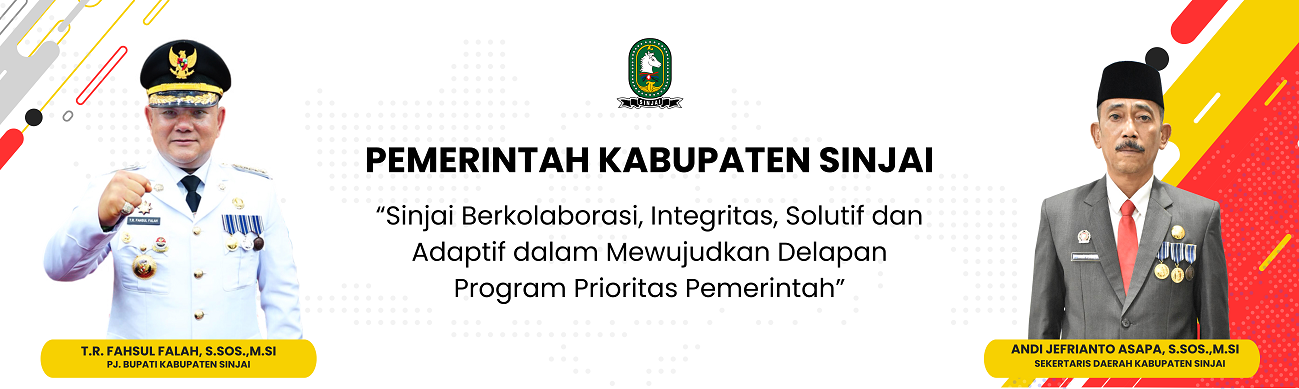Opini
Kisah Seorang Anak Desa Pertahankan Sawah Sebagai Aset Kehidupan

Garut, Beritanasional.ID – Sejak itu saya ikut senang kamu bisa menguliahkan anakmu, tapi kalau bisa tolong jangan sampai jual sawah buat biayanya ya, hal tersebut salah satu pesan nenek pada ibu kala itu. Omongan tersebut keluar hanya berselang beberapa hari selepas nenek tahu saya diterima kuliah.
Mulanya, saya mengira jika nenek terlalu sayang jika salah satu sawahnya harus hilang demi biaya kuliah cucu macam saya.
Padahal, di tahun itu, biaya kuliah saya termasuk murah, total hingga lulus tidak sampai 40 juta. Namun ada salah seorang tetangga yang anaknya masuk SMA favorit bahkan harus membayar 9 hingga 10 Juta Rupiah hal itu sangatlah mahal dibanding biaya masuk kuliah saya. Saking murahnya, beberapa orang mengira universitas tempat saya akan berkuliah adalah kampus tidak jelas atau abal-abal.
Saya memang akhirnya kuliah di kota dan biaya didapatkan tanpa harus menjual sawah. Seiring berjalannya waktu, saya harus merevisi dugaan saya pada nenek perihal permintaannya agar sawah tidak dijual bukan dilandasi rasa pelit. Saat itu, nenek punya sawah sekitar total 10.000 meter di beberapa lokasi.
Untuk ukuran zaman sekarang, angka itu tentu saja besar. Misalkan harga per meter dipatok 200 ribu rupiah, maka nenek punya harta senilai 2 miliar rupiah. Angka yang fantastis dan lebih dari cukup bahkan untuk mendaftar di akademi militer, misalnya. Namun, nyatanya, bagi orang-orang desa seperti nenek, sawah bukan sekadar hamparan tanah dengan aneka tumbuhan. Sawah, bagi orang desa, lebih besar dibandingkan semua itu.
Ibu membuka cerita tentang masa kecilnya. Konon, nenek dan mendiang kakek punya sawah lebih luas dibanding hari ini. Namun, untuk mendapatkannya tidak lewat konsep pengumpulan kapita ala masa kini. Tidak ada cerita kakek dan nenek menabung lalu membeli sawah dan kian lama kian luas. Semua dimulai dari warisan turun temurun. Angka 10.000 meter tadi adalah akumulasi warisan milik kakek dan nenek.
Terdengar sepele dan mungkin akan dikatakan “oh ternyata warisan” oleh anak-anak muda kiwari. Tetapi, di warisan itulah kakek dan nenek benar-benar menggantungkan kehidupan keluarga mereka kelak, bahkan hingga lintas generasi. Apakah semua proses itu dijalani semanis mimpi orang-orang modern untuk menjadi petani penuh waktu di masa tua? Tidak.
Masih kata ibu, kakek bahkan masih terus mencari tambahan pemasukan dengan menjadi petani penggarap di sawah milik orang lain. Sementara nenek juga membantu menambah penghasilan dengan berdagang di pasar pada waktu-waktu tertentu. Dari semua upaya itu, keluarga mereka bertahan dan bisa membangun rumah sendiri di tahun 50-an.
“Hidup di zaman itu susah,” kata ibu. Iya, semua orang rasanya pernah dengar kalimat klise satu ini. Ibu melanjutkan ceritanya bahwa kakek memilih hidup prihatin. Salah satunya, supaya sawahnya tidak berkurang dan ia bisa memberikan warisan yang cukup untuk anak-anaknya kelak.
Urusan hidup prihatin dan mempertahankan sawah punya relevansi dalam betapa susahnya hidup di masa itu. Ibu menuturkan, dulu banyak oknum orang kaya yang gemar bersikap baik saat seseorang hendak meminjam suatu barang. Beras dan bahan makanan adalah benda yang lumrah dijadikan komoditas pinjaman.
Apalagi di musim paceklik. Namun, kebaikan itu tentu saja hanya modus. Ketika akumulasi pinjaman semakin banyak dan si peminjam kesulitan membayar, maka orang kaya tadi tidak segan-segan meminta sawah atau tanah sebagai pengganti hutang. Tentu saja, ini lebih dekat ke aroma perampasan dibanding akad perdata. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada pula perhitungan yang sesuai.
Untuk alasan yang sama pula, kakek lebih memilih mencari tambahan pekerjaan sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Dengan cara ini, ia ingin menghindari jebakan para lintah darat tadi. Semua kembali lagi supaya sawahnya tidak hilang sedikit demi sedikit karena terkena jebakan hutang berkedok kebaikan. Apalagi, beberapa lintah darat tidak segan berbuat kejam jika si peminjam tidak mau merelakan sawah atau tanahnya.
Ibu lantas memberikan contoh beberapa orang yang pernah mengalami kejadian macam itu. Seorang tetangga misalnya, ia bisa punya satu petak sawah sekitar 300 meter di ujung dusun, jauh dari sawahnya yang lain dan berada di sudut petak milik orang lain. “Coba bayangkan, kok bisa punya di sana? Ya karena hal semacam itu tadi,” terang ibu.
Kembali ke soal saya kuliah. Saya kian menemukan jawaban dari sikap nenek dalam suatu fragmen cerita di pertengahan dekade 90-an. Cerita tersebut tentang salah satu adik ibu yang diterima kuliah di sebuah universitas negeri. Kala itu untuk membiayai, bahkan, kakek lebih memilih menjual asetnya yang lain, termasuk pepohonan di kebun, dibanding menjual sawah.
Kemudian pada waktu itu, ibu menyudahi cerita nostalgianya. Saya mulai bisa membayangkan mengapa nenek melarang ibu menjual sawah. Karena, jangankan untuk seorang cucu, mendiang suaminya saja tidak mau menjual sawah bahkan ketika anak kandungnya diterima kuliah. Namun, sekali lagi, itu hanya salah satu alasan saja. Masih banyak alasan lain di alam pemikiran orang desa macam nenek.
Bagi nenek, sawah sudah menjadi bukti jungkir balik kehidupannya selama ini. Mulai dari ia masih gadis, menikah, berjualan beras dan jagung di pasar, membesarkan anak, dan kini menikmati hari tuanya yang mungkin tidak seindah mimpinya dahulu kala. Agaknya pula, sawah menyimpan banyak kenangan tentang mendiang kakek. Sebab, di berbagai cerita soal sawah nenek kadang menyelipkan cerita lewat tuturan, “Kalau kakekmu dulu”.
Saya akhirnya sadar, menjual sawah bagi orang desa bukan sekadar menjual salah satu aset keluarga melainkan menjual kantong-kantong air mata dan darah pengorbanan berpuluh tahun lintas generasi. Untuk membuat saya semakin paham, ibu mengajak saya membayangkan. Betapa durhakanya anak yang sesuka hati menjual sawah milik orang tuanya.
“Dia tidak merasakan perjuangan mempertahankannya di masa sulit. Sekarang ketika dia diwarisi malah sesukanya menjual,” kata ibu. “Ingat ya, hanya diwarisi, tidak beli, tidak susah payah dan tidak berbuat apa-apa.”
Ketika sawah terjual, saya lantas membayangkan perasaan orang-orang tua di desa. Di sana ada kebanggaan pribadi, perjuangan panjang, saksi hidup, sekaligus setumpuk harapan untuk masa mendatang. Namun, itu tentu saja hilang ketika akad jual beli ditandatangani si anak. Semua tinggal cerita dan apa yang bisa dilakukan hanyalah mengisahkan. “Dulu, itu sawah keluarga kita,” mungkin begitu kata-katanya.
Kata ibu, menjual tanah dan sawah juga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Katanya, tidak akan terasa saat sawah dilepas satu per satu, sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba habis tanpa terasa. Saya membayangkan ini seperti permainan monopoli kala saya kecil. Tanpa sadar kartu kepemilikan negara hilang dan tiba-tiba kalah. Lagi-lagi, ibu melengkapi ceritanya dengan contoh dari orang-orang terdekat kami.
“Coba lihat, ada tidak yang jadi kaya karena menjual tanah warisan?” tanyanya. Dan benar saja, saya teringat beberapa tetangga yang hampir semua sawahnya habis terjual dalam waktu tidak sampai 10 tahun.
Dari semua cerita tadi saya lantas teringat betapa pedih cerita para petani tua dulu yang ada di Kabupaten Garut, Jawa-Barat. Disini Media mungkin hanya mampu membingkai perlawanan mereka, dari beberapa pihak mungkin pula menuduh mereka tidak mendukung pembangunan. Di luar semua itu, mereka tidak pernah bisa merangkum kisah-kisah orang desa yang telah terukir di hamparan sawah.
Penolakan dan perlawanan mereka bukan didasari atas kondisi masa kini. Melainkan, ada upaya mempertahankan kisah sejarah komunitas mereka sekaligus upaya meninggalkan kehidupan layak bagi keturunan mereka kelak. Di barisan perlawanan itu, mereka sekuat diri mempertahankan akar sosial dan kebudayaan selama ratusan tahun lamanya.
Apalagi, pengalaman telah mengajarkan betapa desa, tanah, dan sawah mampu menghidupi mereka dari sekian generasi sebelumnya. Tanpa harus ada perubahan berlapis semen dan berlabel pembangunan.
Saya bisa saja mempelajari alasan nenek melarang menjual sawah dari teori sosiologi. Tetapi, sesungguhnya perlu waktu hampir 4 tahun lamanya untuk memahami secara lebih utuh. Untuk itu, saya membandingkan nenek dengan seorang perempuan tua penjual makanan dekat kampus yang pernah bercerita tentang mahalnya harga beras. Iseng saya bertanya apakah ia dulu punya sawah.
“Dulu punya, sekarang jadi tempatmu kuliah itu, dibeli buat dijadikan kampus,” tuturnya dengan mata menerawang. Sementara nenek, sesekali masih bisa memberi uang ke anak cucunya dengan uang hasil panen. Sesekali pula matanya berbinar saat mendengar panen menjelang dan tanpa ada hama menyerang.
Saya juga teringat dengan seorang perempuan tua yang rumahnya sering saya lewati kala kuliah. Di pagi hari, ia biasa menyapu halaman rumah dengan tatapan sendu. Nenek tentu masih beruntung, ia bisa sesekali berjalan-jalan ke sawah untuk menengok padi.
Namun, orang-orang seperti nenek dan ibu tentu akan segera tertelan zaman. Manusia modern yang tidak pernah mengalami hidup susah akan menganggap sawah sebagai sumber aset. Sementara negara mungkin menatap sawah sebagai lokasi pembangunan strategis untuk aneka kebutuhan. Pelan namun pasti, sawah akan terdesak keramaian zaman.
Sebaliknya, di antara gemuruh zaman pula, orang-orang polos nan lugu di desa. Apabila merujuk ke sebutan orang kota, malah mampu melihat dan memahami sawah secara lebih utuh dan bijaksana. Mereka tidak pernah menganggapnya sebagai aset kapital, tidak pernah pula menyayangkan kenapa tidak ada pabrik di desanya. Dari mereka, kita semua seharusnya belajar. Bahwa, sawah bukanlah sekadar lahan untuk ditukar iming-iming oleh dalih yang namanya pembangunan. ( Penulis Diky Kusdian )
Mulanya, saya mengira jika nenek terlalu sayang jika salah satu sawahnya harus hilang demi biaya kuliah cucu macam saya.
Padahal, di tahun itu, biaya kuliah saya termasuk murah, total hingga lulus tidak sampai 40 juta. Namun ada salah seorang tetangga yang anaknya masuk SMA favorit bahkan harus membayar 9 hingga 10 Juta Rupiah hal itu sangatlah mahal dibanding biaya masuk kuliah saya. Saking murahnya, beberapa orang mengira universitas tempat saya akan berkuliah adalah kampus tidak jelas atau abal-abal.
Saya memang akhirnya kuliah di kota dan biaya didapatkan tanpa harus menjual sawah. Seiring berjalannya waktu, saya harus merevisi dugaan saya pada nenek perihal permintaannya agar sawah tidak dijual bukan dilandasi rasa pelit. Saat itu, nenek punya sawah sekitar total 10.000 meter di beberapa lokasi.
Untuk ukuran zaman sekarang, angka itu tentu saja besar. Misalkan harga per meter dipatok 200 ribu rupiah, maka nenek punya harta senilai 2 miliar rupiah. Angka yang fantastis dan lebih dari cukup bahkan untuk mendaftar di akademi militer, misalnya. Namun, nyatanya, bagi orang-orang desa seperti nenek, sawah bukan sekadar hamparan tanah dengan aneka tumbuhan. Sawah, bagi orang desa, lebih besar dibandingkan semua itu.
Ibu membuka cerita tentang masa kecilnya. Konon, nenek dan mendiang kakek punya sawah lebih luas dibanding hari ini. Namun, untuk mendapatkannya tidak lewat konsep pengumpulan kapita ala masa kini. Tidak ada cerita kakek dan nenek menabung lalu membeli sawah dan kian lama kian luas. Semua dimulai dari warisan turun temurun. Angka 10.000 meter tadi adalah akumulasi warisan milik kakek dan nenek.
Terdengar sepele dan mungkin akan dikatakan “oh ternyata warisan” oleh anak-anak muda kiwari. Tetapi, di warisan itulah kakek dan nenek benar-benar menggantungkan kehidupan keluarga mereka kelak, bahkan hingga lintas generasi. Apakah semua proses itu dijalani semanis mimpi orang-orang modern untuk menjadi petani penuh waktu di masa tua? Tidak.
Masih kata ibu, kakek bahkan masih terus mencari tambahan pemasukan dengan menjadi petani penggarap di sawah milik orang lain. Sementara nenek juga membantu menambah penghasilan dengan berdagang di pasar pada waktu-waktu tertentu. Dari semua upaya itu, keluarga mereka bertahan dan bisa membangun rumah sendiri di tahun 50-an.
“Hidup di zaman itu susah,” kata ibu. Iya, semua orang rasanya pernah dengar kalimat klise satu ini. Ibu melanjutkan ceritanya bahwa kakek memilih hidup prihatin. Salah satunya, supaya sawahnya tidak berkurang dan ia bisa memberikan warisan yang cukup untuk anak-anaknya kelak.
Urusan hidup prihatin dan mempertahankan sawah punya relevansi dalam betapa susahnya hidup di masa itu. Ibu menuturkan, dulu banyak oknum orang kaya yang gemar bersikap baik saat seseorang hendak meminjam suatu barang. Beras dan bahan makanan adalah benda yang lumrah dijadikan komoditas pinjaman.
Apalagi di musim paceklik. Namun, kebaikan itu tentu saja hanya modus. Ketika akumulasi pinjaman semakin banyak dan si peminjam kesulitan membayar, maka orang kaya tadi tidak segan-segan meminta sawah atau tanah sebagai pengganti hutang. Tentu saja, ini lebih dekat ke aroma perampasan dibanding akad perdata. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada pula perhitungan yang sesuai.
Untuk alasan yang sama pula, kakek lebih memilih mencari tambahan pekerjaan sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Dengan cara ini, ia ingin menghindari jebakan para lintah darat tadi. Semua kembali lagi supaya sawahnya tidak hilang sedikit demi sedikit karena terkena jebakan hutang berkedok kebaikan. Apalagi, beberapa lintah darat tidak segan berbuat kejam jika si peminjam tidak mau merelakan sawah atau tanahnya.
Ibu lantas memberikan contoh beberapa orang yang pernah mengalami kejadian macam itu. Seorang tetangga misalnya, ia bisa punya satu petak sawah sekitar 300 meter di ujung dusun, jauh dari sawahnya yang lain dan berada di sudut petak milik orang lain. “Coba bayangkan, kok bisa punya di sana? Ya karena hal semacam itu tadi,” terang ibu.
Kembali ke soal saya kuliah. Saya kian menemukan jawaban dari sikap nenek dalam suatu fragmen cerita di pertengahan dekade 90-an. Cerita tersebut tentang salah satu adik ibu yang diterima kuliah di sebuah universitas negeri. Kala itu untuk membiayai, bahkan, kakek lebih memilih menjual asetnya yang lain, termasuk pepohonan di kebun, dibanding menjual sawah.
Kemudian pada waktu itu, ibu menyudahi cerita nostalgianya. Saya mulai bisa membayangkan mengapa nenek melarang ibu menjual sawah. Karena, jangankan untuk seorang cucu, mendiang suaminya saja tidak mau menjual sawah bahkan ketika anak kandungnya diterima kuliah. Namun, sekali lagi, itu hanya salah satu alasan saja. Masih banyak alasan lain di alam pemikiran orang desa macam nenek.
Bagi nenek, sawah sudah menjadi bukti jungkir balik kehidupannya selama ini. Mulai dari ia masih gadis, menikah, berjualan beras dan jagung di pasar, membesarkan anak, dan kini menikmati hari tuanya yang mungkin tidak seindah mimpinya dahulu kala. Agaknya pula, sawah menyimpan banyak kenangan tentang mendiang kakek. Sebab, di berbagai cerita soal sawah nenek kadang menyelipkan cerita lewat tuturan, “Kalau kakekmu dulu”.
Saya akhirnya sadar, menjual sawah bagi orang desa bukan sekadar menjual salah satu aset keluarga melainkan menjual kantong-kantong air mata dan darah pengorbanan berpuluh tahun lintas generasi. Untuk membuat saya semakin paham, ibu mengajak saya membayangkan. Betapa durhakanya anak yang sesuka hati menjual sawah milik orang tuanya.
“Dia tidak merasakan perjuangan mempertahankannya di masa sulit. Sekarang ketika dia diwarisi malah sesukanya menjual,” kata ibu. “Ingat ya, hanya diwarisi, tidak beli, tidak susah payah dan tidak berbuat apa-apa.”
Ketika sawah terjual, saya lantas membayangkan perasaan orang-orang tua di desa. Di sana ada kebanggaan pribadi, perjuangan panjang, saksi hidup, sekaligus setumpuk harapan untuk masa mendatang. Namun, itu tentu saja hilang ketika akad jual beli ditandatangani si anak. Semua tinggal cerita dan apa yang bisa dilakukan hanyalah mengisahkan. “Dulu, itu sawah keluarga kita,” mungkin begitu kata-katanya.
Kata ibu, menjual tanah dan sawah juga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Katanya, tidak akan terasa saat sawah dilepas satu per satu, sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba habis tanpa terasa. Saya membayangkan ini seperti permainan monopoli kala saya kecil. Tanpa sadar kartu kepemilikan negara hilang dan tiba-tiba kalah. Lagi-lagi, ibu melengkapi ceritanya dengan contoh dari orang-orang terdekat kami.
“Coba lihat, ada tidak yang jadi kaya karena menjual tanah warisan?” tanyanya. Dan benar saja, saya teringat beberapa tetangga yang hampir semua sawahnya habis terjual dalam waktu tidak sampai 10 tahun.
Dari semua cerita tadi saya lantas teringat betapa pedih cerita para petani tua dulu yang ada di Kabupaten Garut, Jawa-Barat. Disini Media mungkin hanya mampu membingkai perlawanan mereka, dari beberapa pihak mungkin pula menuduh mereka tidak mendukung pembangunan. Di luar semua itu, mereka tidak pernah bisa merangkum kisah-kisah orang desa yang telah terukir di hamparan sawah.
Penolakan dan perlawanan mereka bukan didasari atas kondisi masa kini. Melainkan, ada upaya mempertahankan kisah sejarah komunitas mereka sekaligus upaya meninggalkan kehidupan layak bagi keturunan mereka kelak. Di barisan perlawanan itu, mereka sekuat diri mempertahankan akar sosial dan kebudayaan selama ratusan tahun lamanya.
Apalagi, pengalaman telah mengajarkan betapa desa, tanah, dan sawah mampu menghidupi mereka dari sekian generasi sebelumnya. Tanpa harus ada perubahan berlapis semen dan berlabel pembangunan.
Saya bisa saja mempelajari alasan nenek melarang menjual sawah dari teori sosiologi. Tetapi, sesungguhnya perlu waktu hampir 4 tahun lamanya untuk memahami secara lebih utuh. Untuk itu, saya membandingkan nenek dengan seorang perempuan tua penjual makanan dekat kampus yang pernah bercerita tentang mahalnya harga beras. Iseng saya bertanya apakah ia dulu punya sawah.
“Dulu punya, sekarang jadi tempatmu kuliah itu, dibeli buat dijadikan kampus,” tuturnya dengan mata menerawang. Sementara nenek, sesekali masih bisa memberi uang ke anak cucunya dengan uang hasil panen. Sesekali pula matanya berbinar saat mendengar panen menjelang dan tanpa ada hama menyerang.
Saya juga teringat dengan seorang perempuan tua yang rumahnya sering saya lewati kala kuliah. Di pagi hari, ia biasa menyapu halaman rumah dengan tatapan sendu. Nenek tentu masih beruntung, ia bisa sesekali berjalan-jalan ke sawah untuk menengok padi.
Namun, orang-orang seperti nenek dan ibu tentu akan segera tertelan zaman. Manusia modern yang tidak pernah mengalami hidup susah akan menganggap sawah sebagai sumber aset. Sementara negara mungkin menatap sawah sebagai lokasi pembangunan strategis untuk aneka kebutuhan. Pelan namun pasti, sawah akan terdesak keramaian zaman.
Sebaliknya, di antara gemuruh zaman pula, orang-orang polos nan lugu di desa. Apabila merujuk ke sebutan orang kota, malah mampu melihat dan memahami sawah secara lebih utuh dan bijaksana. Mereka tidak pernah menganggapnya sebagai aset kapital, tidak pernah pula menyayangkan kenapa tidak ada pabrik di desanya. Dari mereka, kita semua seharusnya belajar. Bahwa, sawah bukanlah sekadar lahan untuk ditukar iming-iming oleh dalih yang namanya pembangunan. ( Penulis Diky Kusdian )